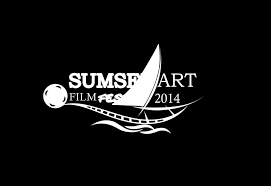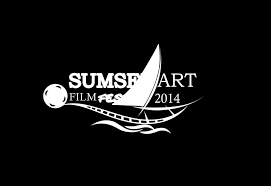Menghormati Sastra dalam Film
Menghormati Sastra dalam Film
Catatan kaki dari perhelatan SAFF 2014
Oleh BENNY ARNAS
Genset yang rusak membuat kereta api yang saya tumpangi menjadi ulat bulu raksasa yang kekenyangan. Perjalanan menjadi sangat lambat dan membosankan (bayangkan saja, hingga pukul lima petang, transportasi publik itu baru tiba di Muara Enim. Ugh!). Tidak ingin menghabiskan waktu dengan mengutuk, saya mengambil laptop dan terdiam sejenak di depan layar monitor sebelum menjentikkan jemari beberapa detik kemudian. Satu jam berikutnya saya pun sibuk dengan keyboard. Menulis memang terapi ketenangan yang menarik dan membahagiakan. Saya perlu menyampaikan ini, sebab movie workshop, movie screening, malam penghargaan film pendek yang baru saja saya ikuti, bukan hanya memberikan ilmu dan energi kreatif berlimpah, tapi juga menyisakan sejumlah kegelisahan yang menuntut untuk saya tuntaskan.
*
Sebagai varian seni yang menghimpun varian-varian seni sebelumnya, film telah tampil sebagai komunikator pesan yang paling efektif. Hal ini menjadi sangat menarik sebab fungsinya yang esensial tersebut, justru tampil dengan pakaian yang bernama hiburan, bukan mikropon sejumlah tujuan. Film dengan cantik menyaru menjadi produk audio-visual yang meminjam varian-varian seni yang lain dengan sangat elegan tanpa harus ‘berutang’ atau ‘mengembalikan’-nya. Sumbangsih varian-varian seni itu pada film, hendaknya tidak dipandang dengan cara yang sangat permukaan: misalnya dengan menyebut music scoring sebagai sumbangan dari seni musik atau roll-player dari teater atau juga skenario dari sastra. Mengapa? Sebab semua varian seni itu sejatinya menjadi penyumbang ruh yang begitu subtil bagi lahirnya film. Dan sastra, sebagai varian seni yang dengan rela—dan atau ‘dipaksa’—oleh film untuk membersamainya dalam melahirkan karya bergerak audio visual, sejatinya menjalari sekujur tubuh film dalam bentuk yang penuh.
Salah satu hal yang sangat menonjol dari kemunculan sastra dalam film adalah metafora yang kerap menurun menjadi semiotika, simbol-simbol yang bukan hanya menjadi keseksian sebuah cerita dengan berbagai kemungkinan tafsir dan kedalaman makna sebuah cerita, tapi juga disebabkan film dan sastra mengimani hal sama: bahwa karya yang baik adalah menunjukkan (to show), bukan menceritakan (to tell).
Dalam konteks ini, film dituntut mampu memanfaatkan ruang dan waktu sebagai keterbatasan yang dimilikinya (bila dibandingkan dengan seni sastra atau rupa, misalnya) agar setiap adegan yang dijahit mampu bercerita dengan lihai dan memandaikan khalayak, bukan menjelas-jelaskan sebuah metafora (atau filosofi atau semiotika atau simbol atau analogi) yang diketengahkan seolah-olah khalayak adalah para penonton yang tidak pandai. Tentu saja beban untuk menampilkan hal itu dengan baik menjadi sangat tidak mudah bila harus dihadapkan pada film pendek dalam durasi antara 15-25 menit (anggap sajalah begitu, meskipun film pendek tidak memiliki durasi yang terpakemkan). Tersebab oleh keterbatasan itu, ide cerita adalah tonggak penting sebelum film diproduksi. Hal inilah yang sepertinya tidak disadari oleh sebagian besar penulis cerita film, termasuk film pendek.
Dalam perhelatan Sumsel Art Film Festival (SAFF) 2014, dari 22 film pendek yang ikut serta, penulis hanya mencatat Kemban 91DB, film tentang penari tunarungu dengan kemban (sejenis songket) sebagai ‘properti’ utamanya, sebagai film pendek paling ‘Timur’ dan semiotis. Kemban 91DB bukan hanya tampil sebagai film pendek yang ‘menghormati’ sastra dari segi ide cerita, tapi juga secara metafora. Film ini berkisah dengan cara visual (showing), bukan memberi pelajaran dengan menjelas-jelaskan (telling) yang justru melemahkan posisi film sebagai produk paling ‘purna’ dari varian-varian seni sebelumnya. Kesastraan Kemban 91DB tidak ditemui di Kuntau, Film Terbaik SAFF yang dengan innocent tampil sebagai film promosi kebudayaan (dan ini menurut saya menyedihkan) atau bahkan Pempek dan Cuko yang begitu genit menjelas-jelaskan analogi pempek dan cuko dengan verbal, terang, dan begitu permukaan (bila masih harus menjelas-jelaskan, untuk apa sebuah analogi, pun sebaliknya?).
Tentu saja, esai ini tidak dalam kapasitas mengkritik hasil penilaian dewan juri sebab penilaian mereka yang didasarkan pada pengetahuan-pengalaman-selera tidak dapat diganggu-gugat, juga bukan saja sebab penulis sendiri tidak keberatan dengan Kuntau sebagai pemenang kompetisi film pendek itu sebab film produksi Marsmallow Photography itu benar-benar memukau dari semua aspek non-kesastraan (meskipun capaian Pempek dan Cuko dengan muatan sastra yang gagal divisualkan sebab harus meminjam mulut salah tokoh “Emak” untuk menerang-nerangkan makna pempek dan cukonya harus menyaru menjadi salah satu pemenang).
Kenyataan yang penulis tangkap di atas, menunjukkan bahwasanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan dan Komite Film Dewan Kesenian Sumatera Selatan sebagai pihak penyelenggara tidak memberi ruang, atau tidak memandang, atau bahkan abai memetakan sastra dengan layak dalam tubuh film. Hal ini, sejatinya bukan hanya tampak dalam kompisisi juri: Jeber (akademisi perfilman), Erwan Suryanegara (Sejarawan dan Perupa), dan Ikhsan (praktisi film), tapi juga ‘terbaui’ ketika rangkaian acara menuju Festival Film Indonesia (FFI) 2014 tidak memasukkan Lomba Kritik Film sebagai salah satu mata acaranya—sebuah kenyataan miris yang mestinya ditangkap oleh insan perfilman sebab berkarya tanpa kritik sama saja membiarkan anak-anak kreatif menjadi liar di dalam rumahnya sendiri. Penyelenggara tampaknya lupa, bagaimana perhelatan sekelas Eagle Award dan FFI dua tahun terakhir (2012-2013) selalu menempatkan sastrawan Leila S. Chudori sebagai perwakilan jiwa sastra dalam panel jurinya, bagaimana maraknya karya sastra (novel) diadaptasi ke layar lebar, atau bagaimana Garin Nugroho memfilmkan puisi-puisi dengan bersahaja sehingga kelirisan dan kesubtilan sebuah metafora membuat penonton kritis, bukan menjelas-jelaskan semiotika yang justru gagal untuk menjadi semiotika itu sendiri.(*)
BENNY ARNAS, Penyuka Film
Tokoh Muda Sastra Indonesia 2014 Pilihan Jawa Pos
Esai ini pernah tayang di Sumatra Ekspress Edisi 4 Desember 2014