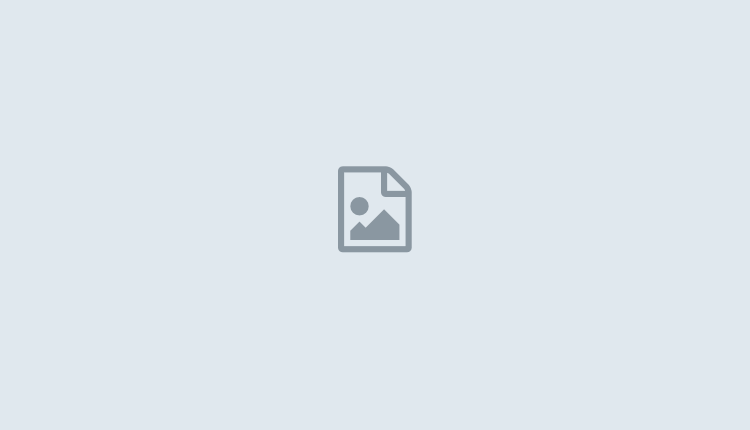Ranting
Ranting, hilang !
Dalam senja yang resah. Terangnya terjepit gelisah.Suara azan melengking di ujung toa. Kemana resah ini kan kulabuhkan? Kepada senja yang kian menepi, atau kepada tabir malam yang kian menanti.Oh, Ranting. Kemana dirimu hendak kucari. Bila di ujung muara kan kutemui, takkan kubiarkan kau lesap diam-diam pergi lagi, lalu kembali bersama air mata yang menggenang dalam perigi.
***
Tanah Melayu, 1975
“Hei, Sialang. Nak kemane kau sinje bute macam nih? apa awak tak dengar kumandang azan dari surau?”
“Iye, Mak. Sebentar saye nak nambat perahu ketek dulu.”
Bagiku, Ranting adalah bidadari kedua setelah Emak. Usia kami hanya selisih lima tahun. Satu hal yang semakin membuatku mengerti, bahwa usia dua puluh lima ini, menjadi semakin menjengkelkan. Karena cericit burung, cahaya kunang-kunang, terasa begitu berbeda. Tak ada lagi Sialang dan Ranting, yang berlarian di tengah hujan dengan bertelanjang dada, tak ada lagi untaian kembang durian yang menguarkan wangi yang bisa kukalungkan di lehernya yang masih berdaki. Mata bocah kami selalu tajam seperti badik, manakala bapak menjemput kami di tengah padang sambil membawa sebilah bambu.
Terkadang aku lelah harus menjadi lukisan abstrak baginya. Aku menjadi sedemikian kejam, cukup lama kubiarkan hatinya tersaput kabut. Dia selalu menerka kelam, sebenarnya aku ini masa lalu yang mengukir senyum, ataukah masa depan sebagai penghapus air matanya. Ranting telah pergi, mungkin hatinyapun telah mati, sejak seluruh warga mengantarkannya ke pondok pengasingan. Kala itu, Sialang tidak ubahnya hanya seorang lelaki sialan.
Mungkin di matanya, aku tak ubahnya hanya seperti kerbau yang di cucuk hidung.Saat para tetua kampung memintaku mengantarkannya dengan perahu menuju pondok pengasingan di hilir sungai.
“Ranting, cakap lah sesuatu. Kediaman awak macam badik yang menusuk tajam tepat di jantungku. Bila awak nak, izinkan saye memutar haluan perahu nih. Kite lawan arus ke hulu.”
“Tak perlu, Lang. biarkan saye menikmati takdir. Harusnya, awak senang, tak akan ada lagi yang memukul, tak ada lagi yang memaksa meletakkan sarang tabuan di atas kepala awak.Lantaran awak bernama sialang,awak harus kuat laksana nama awak, bak pohon sialang yang menjulang, yang menjadi satu-satunya pohon ternyaman bagi tabuan untuk bersarang. Wak Sudir, pasti bangga pada awak, Lang. kerana hari ini awak tak menolak titah para tetua kampung. Walaupun saye tahu, setelah saye pergi, sama artinya separuh sejarah kehidupan awak pun ikut pergi.”
“Kite masih bise mengubah takdir, Ting. Izinkan saye menjadi warga yang tak patuh, kali ini saje.”
Suasana hening. perahu yang kukemudi kian melaju. Sesekali percik air sungai membentur ujung perahu dan bulir bening itu membaur di pipi Ranting yang sudah tak merona. Sesekali kulihat dia menyelipkan lipatan kain sarungnya pada bagian perutnya yang membuncit.
***
Tidak kuat, aku mulai terisak. Bergetar.Aku dengan jelas melihatnya di sini. Meski dia tidak tahu. Aku luka dari dalam. Berkali aku hanya bisa memaki diri. Aku hanya pecundang di mataku sendiri. Saat aku menyaksikan dirinya terhuyung diseret, dibentak, diinterogasi seperti maling. Seminggu yang lalu, aku hanya pecundang di mataku sendiri saat menyaksikan semua itu terjadi.
“Tak ade yang lebih paham kesucian anak kami, duapuluh empat jam kami bersamanya, tak mungkin anak kami, Ranting, berbuat hal yang dapat merusak nama baik kampung nih.” Uwak Abdul, dengan segenap upaya membela.
“Maaf, Cik Abdul. Kami juga tahu itu.Tapi, Cik kan tahu sendiri, ini sudah menjadi tradisi di kampung kite, bahwa setiap masalah yang menyangkut nama baik kampung, pun harus diselesaikan dengan cara adat kampung. Anak awak, Ranting. Mengandung sebelum ada ikatan pernikahan.” Ketua adat menjelaskan.
“Tapi!”
“Sudahlah, Ayah. Ranting terime semuenih, saye siap jalani hukuman apepun. Dan,saye, berani bersumpah, bahwa saye, tidak pernah berbuat nista sebagaimana yang masyarakat tuduhkan. Bapak percaya pada Ranting, kan?” ucapnya datar.
Lalu, sebisik suara berhembus di belakang leherku. Merindingkan kulit dan meruntuhkan senyap.
“Awak pun masih percaye pada saye, kan, Lang?”
“Iye, Saye percaye, bahkan lebih dari diri saye sendiri. Tak perlulah saye menoleh siapapun untuk bertanye, kerana itu sama artinya bahwa saye sedang meragu.”
Dia sunggingkan sekilas senyum.
***
Ranting berdiri di tengah alun-alun. Sejenak dia mematung.
“Wahai masyarakat Tanah Melayu nan tercinte. Ape kalian tahu, bahwa tidak ade yang sie-sie dalam semesta ini. Sekalipun sampah, bau dan kuman. Saye juge mengerti, bahwa kite mempunyai batasan untuk mengetahui berbagai hal. Kite mempunyai due mate untuk melihat, kerananye, kite tak bise melihat dunia hanya dengan satu jendela. Kite mempunyai due telinge, namun kite harus bise membedakan berbagai gaung, bahkan pada saat yang bersamaan. Dan hari ini. Saye, Ranting. Bersedie menerime hukuman apepun, hanya dengan satu syarat, beri sayesatu kesempatan untuk membuktikan kesucian saye.”
Dari kejahuan aku menyaksikannya, dia berorasi bagaikan seorang panglima perang.Masyarakat menjadi riuh.
“Baiklah, Awak berhak mengajukan apepun untuk membela diri awak. Lalu ape gerangan syarat yang akan awak ajukan?”
“Didihkan air sebelange. Dan saye meminta semua lelaki yang ade di kampung nih untuk mencelupkan jarinye. Dengan demikian, terjaminlah kesucian saye, bahwa tak satupun lelaki yang pernah menyentuh diri saye.”
Susana semakin riuh, di mana para kaum perempuan sesaat menjadi ricuh. Setiap anak panah kecurigaan siap melesat dari busur menembus dada para suami dan anak lelaki mereka tanpa ampun lagi.
Gerombolan udara itu tak hentinya menawan berani, satu per satu lelaki harus rela mencelupkan jari, demi mereguk kepercayaan para istri, demi kasih para ibu dan demi sebuah kesaksian suci.
Aku menekuk lututku erat, kupejamkan mata. Oh, segelap inikah?, angin mencengkeram jemariku hangat. Kutarik semua amarah yang masih bersembunyi di bilik-bilik jantung. Saat pelupuk mata kubuka, kuhalau seluruh pekat yang mengental. Kutarik pilu, menatap keliling yang membuta. Aku berdiri, lalu kontraksi ini semakin perih, saat napas sudah tak tergenggam lagi.
“Saye tak bise!”
Dia tersentak. Kutemukan kembaran embun menggulir pasrah di pipi ranumnya.
“Sialang! Ape yang telah awak lakukan? semua orang mencintai saye, membela habis- habisan, mereka menghormati sampai pada batas yang tak bise saye dobrak. Tapi, awak?”
“Ranting, dengarkan saye barang sejenak, saye mengerti diri awak lebih dari mengerti diri saye sendiri. Tapi, bukan begini cara untuk membuktikan kesucian awak. Sejak kecil kite bersahabat. Dengan melakukan tindakan ini, same sajesaye meragukan diri awak , bahkan meragukan diri saye sendiri. Kite tak perlu membuktikan apepun demi sebuah kepercayaan satu sama lain, kerana kite masih punye DIA yang Maha Mengetahui.”
Dia hanya membatu.
***
Seminggu telah berlalu, hari ini aku mengantarkannya menuju pondok pengasingan, sembilan bulan sepuluh hari akan di tempuhinya sendiri. Dan jangan pernah berpikir selama itu aku akan berdiam diri untuknya.
***
Malam ini aku tak bisa tidur, tak bisa memicingkan mata. Bayang –bayangnya mulai merayap di kedalaman hati. Entah bagaimana dia akan melewati serangkaian waktu yang berjarak panjang, sendirian, dalam malam-malam yang lindap dan sepi.
Hari-hari pun sedemikan cepat berlalu. Aku masih diliputi andai-andai. Seandainya aku boleh memilih ke mana aku bisa memutar waktu, aku hanya ingin memilih ke bagian di mana aku masih kanak-kanak bersamanya.Siapa yang bisa menghentikan kiamat kecil ini? Tujuh bulan telah berlalu. Aku sudah terlampau malu karena tak mampu memenuhi janjiku padanya.
Pada pagi yang belia, kukayuh sampan dan kususuri tepian kampung yang masih tersaput kabut. Saat satu tanjung lagi kulewati menuju pondok pengasingan. Tiba-tiba sebuah Sebeng menderu-deru. Dua orang pemuda yang tak begitu jelas wajahnya dan seorang perempuan berkerudung sarung telah berlalu bersama kabut pagi yang semakin abu-abu.
Tajam benar badik yang menghujam jantungku, saat aku menyadari bahwa Ranting telah berlalu pergi. Setapak lagi aku mencapai pondok pengasingan, namun tak ku dapati apapun, bahkan sisa jejaknya sekalipun.
***
Senyap. Satu hurup saja akan guncangkanku lebih dari topan. Sembilan bulan sepuluh hari masa pengasingannya berakhir. Jika aku mempunyai kesempatan untuk bicara tentang kuat, aku tidak mampu. Karena aku tak mampu mendefenisikannya saat harus mengabarkan kepada kedua orang tuanya, bahwa sebenarnya dia sudah tidak ada di pondok pengasingan. Entah di mana,entah bagaimana keadaanya, entah siapa yang telah membawanya.
“Lang!” panggilan Emak membuyarkan lamunanku.
“Cepatlah awak siapkan perahu ketek. Tak ingatkah awak, bahwa hari nih awak nak bawak Wak Cik Abdul, ke pondok pengasingan?”
“Iye, Mak!” aku bahkan tak berani menatap mata Emak.
Ikatan perahu telah kulepas
“Maaf, Wak. Hari nih saye tak bise nak bawa Uwak dengan perahu ketek, kerana dua hari yang lampau, ade due orang dari tanah seberang berniat nak menyewa, jadi hari nih cukuplah kita gunakan sampan , tak pe kan, Wak?”
“Iyelah, Nak Sialang, Tak apelah”
Sampan sengaja kukayuh begitu lamban, sebelum aku kembali menemukan rasa percaya diriku, aku hanya memilih diam. Tak terbayangan olehku, jika nanti, Wak Abdul, harus mengetahui kenyataan ketiadaan Ranting di pondok pengasingan.
Tubuh ringkih lelaki berambut ikal itu, mendarat tepat di depan pondok kecil, dengan tiga anak tangga yang terikat rotan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, beberapa kain lusuh dan sobek terserak, sebentuk tulang pergelangan di sisi kanan pondok menambah remuk hati lelaki tua itu.
“Lang, ape yang sudah berlaku pada anak saye? Tidakkah awak lihat, semue yang jelas di depan mate seperti nih? Kemane gerangan anak Uwak, Lang? Katakan pada Uwak, bahwa Ranting, baik-baik sahaje.”
“Uwak, tenangkanlah diri dahulu, kemarin, saye datang ke tempat nih, saye benar-benar meminta maaf, jike tak izin terlebih dahulu pada Uwak, dan juge masyarakat. Sebelum perahu saye sampai di depan pondok nih, saye melihat ada orang yang membawa Ranting dengan sebeng, saye pun tak tahu mereka siape?”
Aku mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan ke seluruh belukar, berharap ada satu titik pertanda tentang keberadaan Ranting. Tak satupun senyum yang tersisa dari guratan wajah keriput Wak Abdul, yang tersisa hanya geletar tubuh ringkih yang pasrah kupapah menuju sampan.
Aku kembali mengayuh sampan, melawan arus, tidak terbayang rasanya harus mengayuh sampan dalam keadaan seperti ini. Otot, tulang, tenaga bahkan seukir senyumpun terampas sudah.
***
Lima tahun telah berlalu. Kenangan.Memang tak berpungsi apapun selain sebagai pengingat, terkadang menimbulkan berbagai rasa atau bisa jadi membunuh segala keinginan. Seperti kenangan tentangnya, kenangan tentang perjalananku mencarinya hilir mudik, keluar masuk kuala, menyusuri arus dan selat, yang tak tahu bermuara sampai di mana. Seperti yang dikatakan Wak Abdul, pencaharian cukup sampai di sini saja, kita cukup menunggu saja, ya, menunggu saja.
***
Sebentuk kabut meresap, terciumi aroma pagi, kian indah di retina. Sontak, sepasang mataku merekam sosok seorang insan yang tak lagi serupa bayangan mimpi. Sepasang mata dengan garis alis yang dulu mengundang konflik yang tak kunjung redam, lantaran olesan buah kemiri bakar yang kuoleskan diam-diam. Aku tak ingin terpaku terlampau lama.
“Kau kah itu, Ranting?” kataku dalam bisu.
Aku tak lagi menemukan kata-kata, hanya tatap serupa seribu makna, begitupun dengannya, hanya sebingkai senyum penghias wajah.
“Saye pulang, Lang”
“Iye, Ranting.” Mataku nanar.
“Tapi, saye tak sendirian.”
“Oh, Perutmu?”
“Die, Bang Akrom, die yang menemukan saye pingsan di tepian sungai di pondok pengasingan, die bersama rekannya membawa saye ke kota seberang.”
“Lalu?”
“Saye tak mengandung anak siapepun, Lang. Saye sakit.”
“Iya, Bang. Ranting, menderita daging tumboh , dan akar-akarnya sudah menjalar, saya temukan dia di bibir sungai dalam kepayahan, saya putuskan untuk membawanya. Di kota seberang saya mempunyai kenalan seorang ahli bedah.” Lelaki yang di sapa Bang Akrom oleh Ranting, angkat bicara.
“Ayah, di mane, Lang?”
“Sejak awak menghilang, Uwak Abdul, masih terbaring lemah. Masuklah, Ayah awak pasti senang melihat awak datang.”
***
Tuhan tak pernah salah, mungkin memang seharusnya, aku dan Rantingdipisahkan, agar lebih mengerti arti dari sebuah pertemuan dan perjalanan hidup. Bahwa kerinduan adalah sembilu yang teramat tipis. Bahwa benang yang kusutpun lambat laun akan terburai. Dan, fitnah. Takkan pernah menang melawan kebenaran.
(Tugas Kelas Menulis Cerpen daring FLP Jambi)